Ilmu Budaya Dasar; Analisis Film 'Sang Pencerah'
ANALISIS FILM SANG PENCERAH
Film
ini adalah salah satu film megesankan bagi saya yang baru menonton. Kiranya
dari film ini kita bisa menemukan sebuah fakta sejarah yang sulit untuk
dilupakan. Film Sang Pencerah ini
merupakan karya dari sutradara Hanung Bramantyo. Dengan menggunakan
pendekatan kebudayaan, di dalamnya dibahas hubungan antara film sebagai artefak
seni dengan isu-isu budaya, khususnya dalam kaitannya dengan masalah ritual
keagaamaan, dalam hal ini agama Islam. Dalam konteks ini, hubungan antara hati
dan rasio yang menjadi subyek penelitian utama berbanding lurus dengan hubungan
antara tradisi dan modernitas sebagai paradigma zaman. Karena film ini
diciptakan pada era kontemporer, studi atas film tersebut juga dihubungkan
dengan fenomena ritual budaya dan agama saat ini.
Kisah
ini berfokus pada sejarah hidup pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan, sejak
lahir hingga mendirikan Muhammadiyah pada 12 November 1912. Dia beserta 5
muridnya (Sudjak, Fachrudin, Hisyam, Syarkawi, Abdul Ghani). Diceritakan pada
masa itu, masyarakat Yogyakarta khususnya sekitar kraton Yogyakarta masih
percaya dengan hal-hal yang berbau magis. Hal itu disebabkan karena masih
kentalnya adat kebudayaan yang dibawa oleh nenek moyang mereka.
Kepercayaan
animisme dan dinamisme masih hangat terasa pada kehidupan masyarakat daerah
itu. Meskipun mereka telah menganut agama islam namun agama islam yang mereka
anut berakulturasi dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Hal itu
ditunjukan dengan masih banyaknya masyarakat yang masih melestarikan
tradisi kepercayaan animisme dan dinamisme seperti memberi sesaji pada
pohon-pohon yang besar dan menyembah barang-barang yang dianggap keramat.
Sebagian besar mereka masih beranggapan dengan memberikan sesaji diharapkan
hasil panen mereka akan melimpah, jauh dari bahaya malapetaka dan rizeki akan
datang dengan mudah serta melimpah. Tradisi dan kultural tersebut seperti sudah
mendarah daging dan membudaya di masyarakat sehingga sangat susah untuk
dihilangkan. Padahal cara yang dianut masyarakat tersebut merupakan hal yang
sangat menyalahi kaidah dalam agama, menyimpang dari agama terutama dalam agama
islam.
Dalam islam orang yang menyembah selain Tuhan
YME dianggap musyrik. Islam selalu mengajarkan umatnya untuk menyembah dan
percaya pada satu kepercayaan yang dianut yaitu percaya pada Tuhan YME yang
menciptakan alam semesta beserta isinya. Semua anugerah kenikmatan seperti
kesehatan, jabatan dan kekayaan merupakan pemberian Tuhan semata. Selain
masalah diatas hubungan antar masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah
hidup dalam ketimpangan, dimana terjadi ketimpangan masyarakat kelas bawah yang
selalu mengagungkan masyarakat kelas atas, mereka menganggap kelas atas adalah
pemimpin yang harus selalu dihargai, dihormati, disembah dan di agung-agungkan
seperti yang dilakukan masyarakat terhadap seorang kyai atau orang yang
memiliki kedudukan yang berpengaruh tinggi dalam suatu daerah tersebut padahal
belum tentu semua yang dilakukan benar.
Hal
itu terlihat jelas dari masyarakat yang harus merangkak dan bersujud saat
seorang kyai datang. Permasalah-permasalahan seperti ini yang membuat seorang
pemuda tergugah hatinya. Pemuda tersebut bernama Muhammad Darwis. Seorang
pemuda yang menyadari adanya pelaksanaan syariat Islam yang melenceng dari
ketentuan bahkan terbilang menuju kesesatan. Bermodal dari kegelisahan dan rasa
prihatin terhadap keadaan masyarakat sekitar yang masih percaya dengan hal-hal
yang berbau ghoib. Secara tidak langsung mereka telah menyekutukan Tuhan YME.
Mereka telah melakukan serangkaian kegiatan yang bisa dikatakan musyrik. Darwis
pun memutuskan untuk pergi haji ke mekah dan munutut ilmu di Mesir untuk
memperdalam ilmu Islam dan mencari kebenaran tentang syariat Islam yang benar
itu yang seperti apa. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu di negeri orang dan
merasa bekal ilmu yang di dapat sudah dinggap cukup Darwispun memutuskan untuk
kembali ke daerah asalnya Yogyakarta.
Bekal
ilmu agama yang didapatkan diharapkan dapat bermanfaat untuk meluruskan tentang
kaidah dan syariat dalam Islam didaerahnya karena telah melenceng kearah sesat,
selain itu Darwis juga mendapat gelar nama Ahmad Dahlan, nama tersebut
diberikan oleh gurunya. Sesampainya di stasiun dia disambut dengan gembira
oleh keluarganya. Selang beberapa waktu, akhirnya dia menikah dengan Siti
Walidah. Masyarakat menerima kehadiran kyai Ahmad Dahlan dengan baik.
Sepeninggalan ayahnya beliau diangkat sebagai khotib masjid besar yang ada
disekitar Kraton Kesultanan Yogyakarta.
Ahmad
Dahlan memulai pergerakannya dengan mengubah arah kiblat Masjid Kauman. Melalui
pengetahuan geografi yang dimilikinya, Ahmad Dahlan menyadari bahwa arah kiblat
tidak lurus ke arah barat. Hal itu menyebabkan terjadinya kekacauan di dalam
masjid karena ada sebagian jemaah yang mengikuti sholat dari Ahmad Dahlan dan
ada pula yang masih sholat dengan lurus mengarah kiblat. Keadaan ini sontak
saja menjadi pembicaraan para sesepuh. Melihat kekacauan yang ada semakin tak
terkontrol akhirnya para sesepuhpun mengadakan pertemuan dengan
mengundang antara lain semua pengurus masjid dan orang-orang yang memiliki
pengaruh besar dalam masjid untuk membicarakan mengenai perubahan arah kiblat
namun bukanya mufakat yang didapat justru terjadi debat pendapat antar para
sesepuh masjid dalem kraton yang bersikeras menolak pernyataan Ahmad Dahlan
mengeanai pemindahan kiblat. Mereka bersikeras tetap menganggap pendapat yang
dikemukakan Ahmad Dahlan tersebut salah, mereka malah menuduh Ahmad Dahlan
kafir percaya pada setan.
Mereka
juga menganggap peta yang Ahmad Dahlan bahwa itu buatan orang kafir. Sikap
Ahmad Dahlan yang tetap pada pendiriannya memicu kemarahan Kyai Penghulu
Kamaludiningrat yang merupakan kyai penjaga tradisi. Akibatnya, surau milik
Ahmad Dahlan kemudian dirobohkan karena dituding menyebarkan aliran
sesat.
Perjuangan
Ahmad Dahlan semakin berat dan banyak tantangan karena surau milik Ahmad Dahlan
telah dibakar habis. Beliau akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Yogyakarta
bersama istri dan anaknya. Namun niat beliau di halang-halangi oleh
kakaknya, bahkan kakaknya bersedia untuk membangun kembali surau yang telah
dihancurkan. Setelah diberi nasehat oleh kakaknya beliaupun bersedia untuk
kembali untuk mengajar murid-muridnya karena mereka masih sangat membutuhkan
beliau.
Selain
itu menghidar bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada.
Mushola yang telah dibangun diberi nama Ahmad Dahlan yang letaknya didekat
rumahnya. Semakin hari semakin banyak murid yang datang belajar mengaji
dimushola. Metode pembelajaran yang diberikan juga terkesan unik lain dari yang
lain. Berliau mengajar melalui musik biola yang didapat dari pedagang saat
perjalanan kembali ke Yogyakarta. Untuk meredam konflik yang semakin memanas
sultanpun membiayai Ahmad Dahlan untuk pergi berangkat haji kembali.
Sepulanganya dari mekkah aktifitas lain yang dilakukan Ahmad Dahlan, yaitu
membuka sekolah yang menggunakan kursi seperti di sekolah belanda.
Beliau
mengajar dengan benar sesuai kaidah islam, beliau juga mengajarkan kepada
murid-muridnya bahwa agama bukan untuk dihafal tetapi dimengerti dan diingat,
sampai suatu saat kyai bergabung dengan para golongan penggerak Budi Utomo yang
hal tersebut ditentang oleh murid-muridnya karena dianggap golongan tersebut
merupakan para kafir, murid kyai menganggap tidak pantas kyai bergabung dengan
kelompok tersebut karena Ahmad Dahlam seorang kyai sedangkan mereka suka
minum-minuman keras, mabuk dan sebagainya.Selain itu, tuduhan Kyai Kejawen juga
dilemparkan kepadanya karena Ahmad Dahlan dekat dengan cendikiawan Jawa di
Boedi Oetomo.
Berliaupun
menjelaskan kepada muridnya bahwa bergabungnya berliau dengan Boedi Oetomo
semata-mata dengan tujuan hanya untuk belajar tentang bagaimana cara
berorganisasi dan mengenai managemen serta bersosialisasi dalam suatu kelompok
dengan baik, dengan cara menjadi salah satu dari anggota kelompok tersebut dan
dengan mengikuti pertemuan-pertemuan dari itulah beliau belajar. Agar beliau
tidak saja dapat mengetahui tentang ajaran agama islam saja tetapi dapat
mengetahui tentang ilmu yang lain tanpa keluar dari syariat islam bahwa
perlunya pengetahuan tanpa mengabaikan ajaran islam agar masyarakat tidak
menjadi terbelakang tentang pengetahuan yang ada. Pada dasarnya apa yang
dipikirkan berliau bertujuan baik bagi perkembangan islam yang ada di
yogyakarta. Berliau hanya ingin menambah wawasan dengan bergabung pada kelompok
Boedi Oetomo. Namun niat baik seseorang belum tentu baik pula dimata orang
lain.
Banyak
orang yang tidak sependapat dengan berliau bahkan menentang. Hal itu justru
dijadikan pacuan berliau untuk bisa terus maju kedepan meski banyak kerikil
tajam yang menghalangi. Kata putus asa tak pernah terlitas dipikiranya. Selain
itu semua yang dilakukan hanya untuk mempermudah umatnya dalam menerima ilmu.
Melalui metode pembelajaran yang baru diharapkan agar umatnya dapat menerima
ilmu yang di ajarkan dapat diserap dengan mudah serta tidak membuat bosan dan
jenuh. Selama itu tak keluar dari syariat islam. Bukan perjuangan namanya jika
tidak membutuhkan kerja keras.
Semua
penolakan dan tuduhan tersebut tidak membuat Ahmad Dahlan mundur. Dengan
didampingi istrinya –Siti Walidah – dan dukungan lima orang murid setianya —
Fahrudin , Sudja , Sangidu , Hisyam dan Dirjo Ahmad Dahlan membentuk
organisasi Muhammadiyah dengan tujuan untuk mendidik umat Islam yang saat itu
berbaur dengan mistik kejawen agar berpikiran maju sesuai dengan perkembangan
zaman. Melihat kultural masyarakat Yogyakarta yang masih kental, Ahmad
Dahlanpun menggabungkan konsep kebudayaan dengan agama. Dakwah yang dilakukan
mengunakan wayang sebagai media dawah. Berliau berfikir wayang dapat digunakan
sebagai media dakwah karena orang pada zaman dahulu telah mengenal wayang
sehingga akan lebih mudah jika sosialisasi mengenai syariat agama islam akan
mudah dipahami dah diserap oleh pemikiran masyarakat menggunakan wayang sebagai
medianya. Disamping itu cara ini dianggap tidak akan membuat masyarakat menjadi
jenuh dan bosan menerima ilmu yang mereka pelajari. Wayang sejak dahulu memang
media dakwah yang efektif karena agama islam masuk juga menggunakan media
dakwah pertunjukan wayang. Cerita-ceritanya juga kebanyakan masyarakat
menyukainya. Agama islam memang telah masuk lama dalam masyarakat dan sebagian
besar mereka menganut agama islam namun kultur masyarakat masih saja ada.
Kebudayaan
masyarakat jaman dahulu yang menyembah hal-hal yang gaib dan menyembah berhala,
menganggap pohon besar keramat, melakukan sesaji sampai sekarang ini masyarakat
Yogyakarta masih melakukan sesaji untuk terhindar dari bencana seperti sesaji
untuk gunung merapi dan sedekah laut agar diberi keselamatan yang hal tersebut
sudah menjadi tradisi bagi setiap warga Yogyakarta sampai sekarang justru
berbaur terakulturasi dengan ajaran islam, namun walaupun demikian tidak
menghilangkan ajaran agama islam yang dianutnya. Selain menyiarkan agama islam
secara tidak langsung juga melestarikan kebudayan nenek moyang.
Sedikit
demi sedikit usaha yang dilakukan oleh kyai Ahmad Dahlan telah membawa banyak
perubahan. Sebagian masyarakat telah sadar kalau memberi sesaji dan mempercayai
hal-hal yang berbau ghoib merupakan kegitan musyrik yang sangat bertentangan
dengan agama islam. Hal itu sama saja menyekutukan Tuhan YME yang merupakan
satu-satunya penguasa jagad ini. Tuhan yang mencipatakan alam ini beserta isinya.
Masyarakat mulai sadar betapa petingnya agama sebagai pedoman hidup dalam
kehidupan sehari-hari.
Agamalah
yang mampu menuntun orang membedakan mana yang baik mana yang buruk mana yang
benar dan mana yang salah. Agama dan budaya saling berkaitan dan saling
mempengaruhi. Melalui proses sosial dan interaksi yang ada kebudayaan telah
menjadi media penyampaian ajaran agama yang efektif karena pada kehidupan
masyarakat, masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan agama ataupun budaya,
keduanya saling mempengaruhi dan berperan penting dalam akses kehidupan
masyarakat sehari-hari karena fungsi dari kebudayaan itu sendiri untuk
memelihara keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat. Selain itu
lingkunganpun sangat berperan penting dalam pembentukan karakter dan
kepribadian masing-masing masyarakat.
Secara
tidak langsung agama telah menyatukan kultur budaya yang ada didalam
masyarakat sehingga terjadi keharmonisan hubungan antar umat beragama terutama
sesama umat islam, perselisihan yang terjadi dapat diredam seperti yang terjadi
antara kyai masjid besar dengan Ahmad Dahlan yang mengenai ajaran islam,
permasalahanpun dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya pergolakan dan
tanpa ada yang merasa dirugikan karena kerukunan antar sesama umat beragama
merupakan salah satu hal yang diajarkan dalam agama islam. Sebenarnya yang
dibutuhkan yaitu rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain itu
merupkan hal yang terpeting dalam menciptakan suasana yang rukun tanpa adanya
sikap fanatisme yang justru akan menimbulkan konflik yang pada akhirnya justru
memicu adanya perpecahan yang terjadi. Keadaan ini justru akan sangat
merugikan.
Permasalahan–permasalahan
yang ada diatas tidak perlu terjadi jika mereka mau menerima suatu perubahan
selama itu merupakan perubahan menuju arah yang lebih baik dan tidak merugikan
diantara kedua belah pihak. Semuanya itu seharusnya dijadiakan sebuah inovasi
untuk menambah wawasan untuk dikaji lebih jauh dan untuk mendalami tentang
aturan-aturan kaidah dalam islam yang pada akhirnya dapat memperkaya khasanah
sistem spiritual dalam masyarakat. Jika para sesepuh masjid bisa bersikap
terbuka mau menerima perubahan yang terjadi tentu saja perselisihan pendapat
tidak perlu terjadi. Apa yang dikatakan kyai Ahmad Dahlan mengeani arah kiblat
memang benar bahwa arah sholat yang benar lebih condong kekiblat, menyesuaikan
dengan apa yang ada di tanah suci tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT,
berliau berpendapat tersebut disertai dengan argumen yang dapat dipertanggung
jawabkan. Berliau berkata berdasarkan fakta yang ada.
Melalui
media kompas dan peta kita dapat mengetahui arah yang benar bukan berarti kita
kafir percaya dengan hal-hal tersebut tetapi dengan media tersebut kita dapat
mengetahui arah dan petunjuk yang benar seperti yang dilakukan kyai Ahmad
Dahlan tersebut, agar tidak terjadi kekeliruan seperti yang ada ketika belum
adanya perubahan yang dilakukan oleh beliau. Berkat jasa berliau kekeliruan
yang selama ini terjadi dapat diluruskan. Tidak hanya mengenai arah kiblat
namun tentang budaya sesaji yang masih melekat pada masyarakat daerah
Yogyakarta.
Sebagian
besar masyarakat telah menyadari kekeliruan yang selama ini mereka lakukan.
Semakin sedikit masyarakat yang masih menggunakan budaya sesaji menujukan bahwa
Kyai Ahmad Dahlan telah berhasil membawa suatu perubahan yang lebih baik dan
berliau sangat berjasa bagi kehidupan sosial budaya dan agama di daerah
Yogyakarta. Sebagian masyarakat telah menyadari bahwa yang memberikan mereka
kesehatan, rizeki, kekayaan tak lain adalah anugerah dari Yang Maha kuasa bukan
pohon, keris atau benda keramat lainya. Sungguh sangat murah hati Tuhan YME
memberikan anugerah yang tak ternilai harganya. Meskipun begitu tradisi
budaya sesaji sampai saat ini masih berjalan didaerah Yogyakarta. Hal itu mencerminkan
bahwa tradisi tersebut telah membudaya di dalam masyarakat sehingga tidak akan
hilang walaupun sebagian besar telah menyadari jika tradisi tersebut
bertentangan dengan ajaran dan syariat islam. Pada dasarnya kebudayaan suatu
daerah merupakan suatu ciri khas dari daerah itu sendiri dan merupakan hasil
dari masyarakat melalui proses interaksi dan sosialisasi.
Analisis
Struktur
Sang
Pencerah merupakan film dengan teknik penceritaan yang
convensional, yakni mengalur pada plot yang linear dari peristiwa A sampai Z.
Pada alur itu bahkan tidak ditemukan momen flashback, semua peristiwa
dirangkai secara kronologis dari awal hingga akhir.
Struktur
alur demikian dimungkin-kan dipilih Bramantyo karena film ini memang
meceritakan biografi seorang tokoh, yakni kisah tokoh tersebut mulai dilahirkan
hingga momen puncak (pencapaian) tokoh dalam kehidupannya, yakni lahirnya Ahmad
Dahlan hingga berdirinya Muhammadiyah. Dengan demikian, film ini memang tidak
menyoroti konflik batin atau perjalanan spiritual sang tokoh, melainkan lebih
ke arah kisah kehidupan tokoh dalam kaitan dengan perubahan-perubahan sosial
yang terjadi di masyarakat. Dalam perubahan itu, sang tokoh hadir sebagai sosok
yang “mengubah”. Pada konteks ini pun sebenarnya film ini tidak bisa dikatakan
sebagai film “sejarah tokoh” sebab ia hanya mengambil bagian-bagian penting
(pokok soal) dari peranan sang tokoh dalam masyarakat. Kisah kepergian dan
proses belajar tokoh mendalami Islam di Mekkah, misalnya, lebih dihadirkan
secara in absentia dalam benak penonton.
Beranalogi
pada konsep linguistik struktural Ferdinand de Saussure dalam Course in General
Linguistics (1990), secara umum struktur film ini dibangun dalam dikotomi atau
pasangan-pasangan pertentangan (binary opposition). Pasangan-pasangan
pertentangan tersebut antara lain sebagai berikut:
Pasangan-pasangan
pertentangan tersebut menjadi semacam “tulang punggung cerita”. Artinya,
seluruh peristiwa terjadi di atas pasangan pertentangan tersebut atau karena
adanya pasangan pertentangan itu. Konflik berkepanjangan antara Ahmad Dahlan
dan Imam Masjid Besar, misalnya, melahirkan berbagai peristiwa sepanjang
cerita, peristiwa pembakaran Langgar Kidoel terjadi karena kehadirannya—setelah
Ahmad Dahlan menggantikan ayahnya sebagai imam—dianggap menentang Masjid Besar,
dan seterusnya.
Dalam
pendekatan kebudayaan, karya seni, dalam hal ini film, ditempatkan pada ruang
dan waktu ketika karya itu diciptakan, hidup, dan berkembang. Dengan kata lain,
karya seni disikapi sebagai sebuah entitas yang memiliki hubungan dengan
persoalan zamannya. Pada karya-karya tertentu yang gagasan ceritanya lahir dari
fenomena sezaman, hubungan tersebut kiranya tidak terlalu rumit. Di situ, karya
seni bisa dilihat sebagai mimesis (Plato), representasi (Aristoteles) atau,
sebagaimana dikatakan M.H. Abram, dapat disikapi sebagai cermin realitas
(Abrams, 1980: 31).
Akan
tetapi, jika gagasan dasar karya menyangkut sejarah, artinya karya yang lahir
hari ini berisi kisah tentang masa lalu, hubungannya menjadi sangat kompleks.
Apresiator atau periset harus menelaah dua hal sekaligus. Pertama,
bagaimana hubungan realitas yang diceritakan (realitas karya) berhubungan
dengan nilai-nilai budaya sebagai realitas riil (di luar karya). Kedua,
bagaimana pula karya itu berhubungan dengan realitas zaman saat dia diciptakan.
Dalam hal ini setidaknya muncul pertanyaan, mengapa realitas masa lalu itu diwujudkan
dalam karya hari ini.
Sementara
itu, film ini diciptakan pada zaman yang telah jauh berbeda dari realitas
cerita dalam film tersebut, yakni kurang lebih satu abad kemudian. Fakta
tersebut jelas menimbulkan konsekuensi, yakni Sang Pencerah harus
dianalisis dalam dua tahap. Tahap pertama, fakta narasi film harus
dikorelasikan dengan ruang dan waktu riil narasi. Tahap kedua, fakta
narasi film tidak bisa tidak mesti dihubungkan dengan ruang dan waktu riil
ketika film ini dibuat, yakni kondisi zaman hari ini. Sementara itu,
kebudayaan—sebagai ruang dan waktu cerita juga penceritaan film-- secara umum
dapat dilihat dalam dua kategori, yakni kebudayaan benda (material culture)
berupa karya (artifak) yang teraba (tangible) dan kebudayaan non-benda (nonmaterial
culture), yaitu nilai-nilai, pandangan hidup, gagasan, dan lain-lain yang
takteraba (intengible). Namun, kedua hal ini bukan merupakan sesuatu
yang bersifat partikular atau terpisah, melainkan merupakan sebuah kesatuan.
Karya-karya budaya (artifak) umumnya merefer ke berbagai hal di luar dirinya,
yakni pada ranah kebudayaan nonbenda tersebut. Dengan demikian, film Sang
Pencerah sebagai artifak kebudayaan juga berada dalam posisi itu.
Sumber: (http://id.wikipedia.org/wiki/Sang_Pencerah)
Afifi, John. 2011. Pakai Otak Kananmu, Dijamin Kaya.
Yogyakarta: Bening
Barker, Chris. 2005. Cultural Studies, Teori dan Praktik,
terjemahan Tim KUNCI Cultural Studies Centre. Yogyakarta: Bentang.
Berg, C.C. 1974. Penulisan Sejarah Jawa, terjemahan
oleh S. Gunawan. Jakarta: Bharata.
Gee, James Paul. 2005. An Introduction to Discourse
Analysis, Theory and Method. London and New York: Routledge.
Giddens, Anthony. 2003. Masyarakat Post Tradisional,
terjemahan oleh Alie Noer Zaman. Yogyakarta: IRCiSoD.
Pratista, Himawan.2008. Memahami Film. Yogyakarta:
Homerian Pustaka
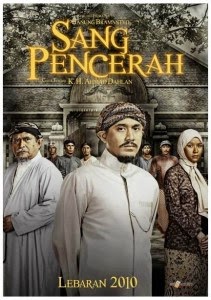

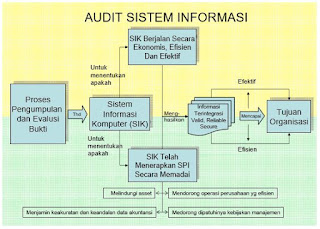
artikelnya sangat bagus lanjutkan.salam st3telkom
BalasHapus